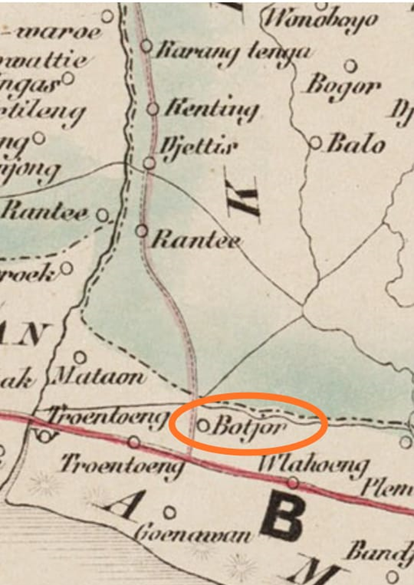BOCOR & DINAMIKA WILAYAH DESA
DI PESISIR SELATAN JAWA; SUATU ESAI
Oleh
Agusta Prihantoro
Pendahuluan
Kabupaten Kebumen terletak di
pesisir selatan Pulau Jawa. Sisi selatannya berbatasan langsung dengan Samudra
Hindia. Dataran landai yang membentang luas ini, telah dihuni oleh manusia
sejak era yang sangat lampau. Pelbagai penemuan artefak menunjukkan bahwa
dinamika historis telah berlangsung sejak era pra-sejarah (Punden Berundak
Lurah Karsa). Dan terus bekesinambungan hingga era saat ini (2022), dengan pelbagai
gejolak sosial, interaksi budaya, serta bencana alam. Semuanya saling
memengaruhi hingga Kebumen menemukan bentuk perwujudan sosial kemasyarakatan
seperti saat ini.
Di sisi barat dan utara, pegunungan
Karangbolong-Karangsambung yang kaya batuan karst, mendominasi lingkungan
alamnya. Namun demikian, di dataran aluvial sisi selatan, Kebumen memiliki
lahan pertanian yang subur. Meskipun pernyataan ini baru bisa diamini saat ini,
karena sisi timur dan barat didominasi oleh kawasan rawa yang masih eksis
hingga 1890-an. Tetapi secara umum wilayah Kebumen saat itu, dapat dikatakan
menjadi lumbung pangan yang sangat potensial. Hal ini lah yang memicu pelbagai
gejolak sosial di kemudian hari.
Di sisi selatan Kabupaten Kebumen,
terdapat Kecamatan Buluspesantren. Di kecamatan ini lah terdapat desa bernama
Bocor. Tentu nama yang sangat unik, sehingga sering dijadikan guyonan kedai. “Kalau
naik motor ke Bocor, jangan takut, nanti lewat Ambal!” Seolah-olah kata
“bocor” disandingkan dengan kata “tambal”, yang pada kenyataannya letak Desa
Bocor memang tak jauh dari kota Kecamatan Ambal. Tentu saja hal itu suatu
kebetulan belaka, dan sudah menjadi materi komedi masyarakat. Dibalik nama
Bocor, terdapat dinamika historis yang sangat kompleks.
Desa Bocor sendiri bisa dicapai melalui
Jalan Diponegoro di sisi selatan. Yakni melalui pertigaan Kantor Kecamatan
Buluspesantren ke arah utara. Atau dari sisi Kota Kebumen, melalui perempatan
lampu merah Desa Muktisari, ke arah selatan hingga sampai di Kali Garung (Kali Kedhungbener),
yang terletak Pasar Bocor di sampingnya. Pasar, industri pandai besi, rumah-rumah
joglo, hingga ternak sapi menjadi branding yang sangat menarik bagi
Bocor.
Di lain sisi, rasa penasaran tentu
sangat menggelitik mendengar kemasyhuran Bocor di era lampau. Sejarah panjang
wilayah Bocor telah lama menjadi perbincangan para ahli. Meskipun terbentur
oleh pelbagai kendala yang menyulitkan upaya rekonstruksi sejarah secara
komprehensif. Misalnya keterbatasan sumber sejarah, kesadaran sejarah
masyarakat yang minim, hingga apatisme birokrasi pada pentingnya kajian sejarah
lokal (local history). Namun, fakta-fakta menarik di lapangan justru
kian banyak yang terungkap. Misalnya penemuan artefak mustaka di Masjid
Bocor, makam kuno, sumur jobong (sumur gerabah), dan bekas-bekas
kemasyhuran kawasan tempa besi yang kini semakin redup tergilas zaman. Itu
semua bak puzzle yang perlu diinterpretasi sehingga dinamika sosial-historis
di Bocor bisa diungkap secara ilmiah.
PERKABARAN
TENTANG BOCOR DARI MASA LALU
Membincangkan Bocor di era sekarang,
tentu berbeda dengan Bocor di era lampau. Bocor saat ini, secara de jure
adalah nama wilayah desa yang ruang lingkupnya di bawah tingkat kecamatan. Dikepalai
oleh seorang kepala desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan
kepala desa (Pilkades). Tetapi bila membahas Bocor di masa lalu, pembatasannya
sangat melebar. Tidak hanya pada lingkup sekecil desa seperti saat ini, namun
lebih daripada itu. Wilayah Bocor meliputi wilayah yang lebih luas, dengan
cakupan kadipaten seperti dalam sumber-sumber tradisional (hikayat,
babad, dsb).
Sumber babad yang menyebut Bocor di
era Kerajaan Pajang adalah Babad Wirasaba. Meskipun Babad Wirasaba itu sendiri
juga relatif baru, namun menyebutkan nama Bocor di era berdirinya Kerajaan
Pajang. Budiono Herusatoto (2008) mengungkapkan bahwa salah satu bupati
Wirasaba (cikal-bakal para bupati Banyumas), yaitu Adipati Warga Utama I meninggal
terbunuh di Bocor. Peristiwa ini terjadi ketika Kerajaan Pajang menganggap
bahwa Adipati Warga Utama I dari Wirasaba ingin membelot dari Pajang, pasca
perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Demak ke Pajang.
Seperti diketahui, Wirasaba menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Kerajaan Demak. Saat Demak berdiri, Wirasaba
di bawah tampuk kepemimpinan Adipati Wira Utama I (Raden Paguwan) dan Adipati
Wira Utama II (Raden Jaka Katuhu). Dan ketika Sultan Hadiwijaya bertahta di
Pajang, Wirasaba dipimpin oleh Adipati Warga Utama I (Raden Bagus Suwarga).
Dalam hikayat, cerita ini sangat
populer. Akibat ulah fitnah Demang Toyareka (adik Adipati Warga Utama I/Raden
Bagus Suwarga), sehingga bupati Wirasaba saat itu, Adipati Warga Utama I, tewas
oleh utusan Pajang di Bocor. Menurut babad tersebut, Adipati Warga Utama I berangkat
pada hari Sabtu Pahing ke arah Bocor. Sedianya ia akan sowan ke Kerajaan
Pajang, namun mampir ke tempat rekan karibnya, Demang Bocor. Di tempat Demang
Bocor, Adipati Warga Utama I dijamu suguhan makan pindhang banyak
(dendeng daging angsa). Berada di pendapa kademangan yang tidak memiliki pringgitan
(tempat beratap yang menghubungkan pendapa dengan dalem ageng/rumah
utama). Sehingga terdapat space ruang tak beratap, yang terkena terik
dan hujan.
Alih-alih menikmati semua suguhan tadi, Adipati Warga Utama I malah
tewas oleh utusan Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Ia dibunuh tepat berada di
rumah Demang Bocor, akibat fitnah Demang Toyareka yang mengatakan bahwa Adipati
Warga Utama I berniat membangkang kepada Pajang. Atas kejadian tersebut, hingga
kini terdapat ila-ila (sumpah/aturan adat) yang tak membolehkan semua
warga keturunan Banyumas untuk berhajat di hari Sabtu Pahing. Tidak pula boleh
memakan daging angsa. Serta tidak diperbolehkan membangun rumah pendapa yang
terpisah dari rumah utama.
Sekelumit kisah di atas menunjukkan
bahwa Bocor telah disebut di era Pajang. Yakni dengan munculnya nama Demang
Bocor terkait peristiwa tewasnya Adipati Warga Utama I. Tetapi nampaknya nama
Bocor juga didapati pada Babad Pasir, yang menceritakan kisah saat berdirinya
Kadipaten Pasir. Sekelumit kisah tentang bangsawan Pasir, keturunan Pangeran
Senapati Mangkubumi, yang menetap di Bocor karena peristiwa penyerangan Pasir
oleh Kerajaan Demak. Sehingga atas uraian ini, pentarikhan Bocor bisa dimulai
di seputar waktu penaklukan Kadipaten Pasir.
Di sisi lain, Babad Tanah Jawi juga
turut menyebut Bocor di era awal Mataram. Dalam kisah babad tersebut disebutkan
bahwa Demang Bocor yang sedianya akan menyampaikan bulu bekti (upeti)
kepada Sultan Hadiwijaya di Pajang, dicegat di Mataram oleh Panembahan
Senapati. Atas bujuk rayu Senapati, Demang Bocor menyatakan kesetiannya kepada
Mataram. Meskipun didahului oleh peristiwa dramatis seperti diungkapkan babad. Demang
Bocor sempat menjajal kesaktian Panembahan Senapati dengan Keris Mahesa Dengen.
Tetapi penguasa Mataram terlampau sakti. Ia kebal terhadap keampuhan keris
Demang Bocor.
Dalam babad yang lebih baru (Babad Arung
Binang versi Mangunsuparta, 1937), disebutkan suatu peristiwa yang menyebut
nama Bocor lagi. Yaitu Demang Prawiragati dari Pekacangan (dekat Jembangan saat
ini) mengutus seseorang untuk mencuri keris sakti milik Ngabei Bocor. Yang
bernama Kiai Pandu, berdapur Sinom. Setelah keris berhasil dicuri, utusan tadi
mampir di rumah teman di Kutowinangun. Ternyata utusan disiksa oleh temannya. Demang
Prawiragati marah, merasa bahwa utusannya telah disiksa oleh suruhan Demang
Hanggayuda (Demang Kutowinangun). Sehingga Demang Pekacangan menyerbu
Kademangan Kutowinangun. Atas penyerangan yang tanpa aba-aba ini, Demang
Hanggayuda terpaksa menyingkir ke Ngabean. Sembari membangun kekuatan pasukan
yang dipimpin oleh Raden Surawijaya (Joko Sangkrib).
Kisah-kisah babad di atas memang
menyajikan ulasan yang lengkap. Namun sekali lagi, babad atau hikayat bukan sumber
primer dalam studi sejarah. Babad dan semacamnya adalah karya sastra, yang
memuat kisah-kisah khayali seperti kesaktian, fabel, dan makhluk abadi. Sekali
pun babad dijadikan sumber penulisan sejarah, ia akan ditapis sebersih mungkin,
alih-alih menerimanya dengan mentah-mentah. Begitu pula babad, ia akan ditemukan
dalam banyak versi. Seperti Babad Banyumas, Sugeng Priyadi mengungkapkan ada
banyak versi Babad Banyumas yang memiliki sudut pandang masing-masing. Sehingga
semakin nampak bukti bahwa produk sastra seperti babad adalah alat untuk
menciptakan kekuatan hegemoni atas klan-klan atau wangsa yang berkuasa/menang.
S. Margana (2010: 1) mengungkapkan
dalam alih aksara atas arsip keraton Surakarta-Yogyakarta, tentang suatu hal
yang menarik. Arsip ini merupakan catatan
tentang pembagian wilayah kerajaan, struktur birokrasi, dan nama-nama kesatuan
prajurit Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma
(1613-1645). Pada tahun 1636, Sultan Agung Hanyakrakusuma mulai membentuk dan
mengatur birokrasi kerajaan yang terdiri dari 16 pejabat Bupati Nayaka
Jawi-Lebet, serta membagi tanah pedesaan di luar wilayah inti (Negara
Agung), yang bukan merupakan wilayah mancanegara.
Di dalam alih aksara disebutkan
bahwa tanah di Bagelen dibagi menjadi dua (2) bagian. Sebelah barat disebut Siti
Sewu, yang meliputi Sungai Bagawanta ke barat mengikuti Dhudhuwala (Wala?),
Telaga (Mirit), Bulu Kapitu (Kutowinangun), hingga Dhadhap Agung (Cidadap,
Karangpucung, Cilacap?). Sedangkan di timur disebut dengan Siti Numbak Anyar,
dari Sungai Bagawanta ke arah timur hingga Sungai Praga. Atas dasar ini, bisa
ditarik kesimpulan bahwa wilayah Bocor menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
Mataram. Mengingat Bocor menjadi bagian dari Siti Sewu. Toponimi Siti
Sewu ini yang kemudian terpatri dalam memori kolektif masyarakat Kebumen. Sehingga
untuk menyebut wilayah Kebumen di pesisir selatan sering dinamakan Urut Sewu.
Daerah pertanian yang subur di sepanjang pesisir dikelola oleh
masyarakat yang ulet dengan pelbagai pekerjaan pertanian yang berat. Dari dulu
penduduknya ulet dan tidak mudah menyerah. Semangat seperti ini nampaknya
memiliki akar sejarah yang kuat di masa lalu. Buktinya, wilayah Siti Sewu
di era Mataram (dan Kartasura) menjadi penyokong utama bau-suku (pekerja)
bagi kepentingan kerajaan yang dikoordinasi oleh abdi dalem Mantri Gowong.
Juga dipimpin oleh pejabat kerajaan, disebut Abdi Dalem Bupati Nayaka Jawi
Tengen. Menurut naskah alih aksara No. 4, S. Margana (2010: 10-11)
menerangkan bahwa di era Susuhunan Pakubuwana II (1726), bupati nayaka Siti
Sewu adalah Kiai Tumenggung Anggawangsa (RT. Arungbinang I/Joko Sangkrib),
nama yang kerap dielu-elukan sebagai leluhur/cikal bakal Kebumen.
Bocor merupakan bagian dari Siti Sewu seperti diungkapkan di
atas. Keberadaannya saat ini (yang hanya tinggal seluas desa), telah dimulai
secara terstruktur di era Mataram. Dengan jelas digambarkan hubungan Mataram
dengan Bocor, sebagai wilayah di tanah Bagelen. Namun demikian, sumber Belanda
juga patut kita telusuri untuk merangkai fakta-fakta sehingga lebih obyektif.
Bocor juga muncul dalam beberapa
surat kabar di era Kolonialisme Hindia-Belanda. Salah satunya pada Javasche
Courant, yang terbit pada tanggal 27 Februari 1866. Tentang penjualan aset
gedung milik pemerintah eks-pabrik Nila/Tarum (Indigofera). Di afdeeling Ambal,
salah satunya disebutkan nama Botjor, selain Agliek (Aglik), Ambal, Wlakoeng
(Wlakung), Kedoijo, Mirit, Patoot (Patut), Ngentak (Entak), Gading
(Karanggadung?), dan Morros (Moros, Karangbolong?).
Seperti diketahui, bahwa tanaman Indigofera merupakan komoditas perkebunan yang ditanam pada era Tanam Paksa. Indigofera ini sangat bermanfaat kala itu sebagai pewarna biru alami pada industri tekstil. Pada fakta ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode Tanam Paksa, Bocor menjadi salah satu lokasi penanaman Indigofera bagi pabrik-pabrik milik pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Yang ternyata mendekati 1866 mengalami bangkrut, dan pada akhirnya aset berupa gedung pabrik tersebut dijual/dilelang oleh pemerintah (Residen Bagelen; P.J. Serle).
Dinamika historis ini dapat
dimaklumi bahwa pada era Mataram, Bocor atau Bagelen pada umumnya merupakan kawasan
yang subur. Karesidenan Bagelen (yang akhirnya dihapuskan) menjadi lumbung
pangan sejak era Mataram hingga sekarang. Secara kasat mata seperti dapat
disaksikan saat ini, Bocor yang dilalui oleh Kali Garung (Kali Kedhungbener)
menjadikan kawasan pertanian yang sangat potensial (di masa itu).
Ada juga berita yang menarik serta
perlu disoroti, yaitu tentang organisasi semacam Perkumpulan Aparatur
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), yang muncul di era Hindia-Belanda.
Berita tersebut terdapat pada surat kabar De Locomotief, yang
diterbitkan pada tanggal 21 September 1928, berjudul Loerahbond (Jalinan/Perkumpulan/Serikat
Lurah).
Alih
bahasa:
“Dan di
Kabupaten Kebumen sudah ada federasi kepala desa selama beberapa tahun, yang
tujuannya selain untuk meningkatkan posisi mereka adalah untuk meningkatkan
pengetahuan para anggotanya khususnya tentang masalah desa, sehingga sebagai
kepala desa mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban. Hari-hari ini serikat pekerja
(kepala desa) mengadakan rapat umum bulanan, di mana diputuskan antara lain,
untuk menunjukkan lebih banyak aktivitas demi kepentingan desa. Serikat ini
dipimpin oleh kepala desa Kebumen, Walaija, dan Bocor.” (de Locomotief, 1928)
Pada berita di atas, didapati fakta
bahwa Lurah Bocor merupakan pimpinan pada perserikatan lurah di Kabupaten
Kebumen. Fakta ini menunjukkan peran aktif Bocor di kancah organisasi
pemerintahan desa secara baik (saat itu). Keikutsertaan Lurah Bocor pada
perserikatan Lurah di Kabupaten Kebumen tentu menjadi informasi menarik yang
memberi setitik fakta, bahwa lurah Bocor saat itu menjamin hak dan kewajibannya
sebagai pemimpin Bocor terpenuhi dengan baik. Selain juga upaya meningkatkan kompetensi
lurah se-Kabupaten Kebumen kala itu (1928).
ARTEFAK
BERSERAKAN DI SEKITAR BOCOR
Selain itu di Dukuh Ragayudan, terdapat dua buah sumur kuno. Yang bagian
dinding sumurnya terbuat dari tembikar. Tatanan tembikar pada sumur yang ditata
bersusun ini kerap disebut sebagai sumur kejobong. Dua buah sumur ini
masih dipelihara oleh masyarakat sekitar, dan terletak di pekarangan warga.
Sebagian masyarakat menganggap sumur ini sebagai sumur tiban, yaitu
sumur yang ditemukan oleh masyarakat secara tidak sengaja. Sehingga kemudian
menimbulkan kultus kekeramatan terhadap sumur tersebut.
Dari istilah kejobong,
masyarakat Jawa memberi sebutan terhadap bibir sumur yang lebih tinggi dari
muka tanah sebagai jubung. Meskipun bibir sumur tersebut bukan berasal
dari tembikar/terakota, tetapi batu bata, trebis, atau bahan yang lain.
Sebutannya tetap jubung, sebagai akar tradisi menyebut kejobong. Tembikar
ini secara teknis, sebagai penahan dinding tanah agar tidak gugur ke sumber
air, sehingga menutup sumber. Teknologi kuno ini masih lestari di Jawa,
meskipun penggunaan tembikar telah diganti trebis, sehingga lebih praktis dan
lebih kuat.
Di Desa Ayamputih, dekat Bocor, juga
terdapat peninggalan yang menarik. Di dekat sawah Si Kentheng, terdapat
seonggok fragmen batu yang menurut tutur masyarakat dikenal sebagai Watu
Celeng. Namun demikian, batu tersebut sejatinya merupakan fragmen sebuah
yoni, yaitu artefak keagamaan Hindu. Bagian tubuh yoni terbelah, menyisakan
sebagian badan yoni dan sisi bagian cerat yoni. Cerat yoni ini, dalam pandangan
masyarakat awam dianggap sebagai moncong celeng/babi hutan.
Sementara itu, di sekitar pantai
Bocor juga pernah dilaporkan suatu temuan/struktur batu bata, yang diduga
sebagai benda cagar budaya. Meskipun menurut ahli (Teguh Hindarto, S.Sos.,
M.Th.), lokasi tersebut diduga berasal dari masa awal abad 20, tetapi kajian
tentang temuan-temuan di Bocor dan sekitarnya menjadi sangat menarik, manakala
riwayat Bocor di masa lalu ingin direkonstruksi secara kronologis.
WETAN
KALI-KULON KALI; DIVERENSIASI YANG BERLANJUT
Kabupaten Kebumen saat ini, memiliki luas yang
membentang, di sisi timur Prembun hingga Rowokele di sisi barat. Di selatan
Samudra Hindia dan membentang pegunungan di sisi utara sebagai batas dengan
Banjarnegara. Kabupaten dengan luas yang fantastis ini, sejatinya di masa lalu
merupakan penggabungan dari pelbagai wilayah yang merdeka. Dengan pelbagai
dinamika politik, Kabupaten Kebumen kemudian menemukan bentuknya seperti yang
sekarang ini.
Menurut babad-babad tradisional, wilayah
Kebumen dahulunya terbagi-bagi pada daerah kecil. Dalam Babad Sruni, disebutkan
bahwa di era Amangkurat Agung (Mataram) terdapat wilayah Sruni yang dipimpin
oleh seorang tumenggung. Sruni ini dicapai melalui Klegen Kilang
(Selang) ke arah utara. Begitu pula dalam Babad Karangsambung, di era Amangkurat
Agung, terdapat wilayah Panjer yang dikuasai oleh seorang tumenggung. Dua
lokasi ini terdapat di sisi timur aliran Kali Lukulo, yang merupakan sungai
terbesar di Kebumen. Dan Bocor terletak di sisi timur sebelah selatan
(pesisir), Kali Lukulo.
Di sisi barat, dalam sumber-sumber
tradisional lain, di era Amangkurat Agung terdapat wilayah Rema/Roma. Wilayah
ini sebagai cikal bakal dua kota besar di Kebumen, yaitu Gombong dan
Karanganyar. Wilayah Rema ini secara geologis terletak di sisi barat Kali
Lukulo, dengan cakupan wilayah yang lebih luas, serta budaya masyarakatnya lebih
condong ke arah budaya Banyumasan.
Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa
wilayah Kebumen saat ini adalah eks-Siti Sewu di era Mataram, sebagai
pembagian dari tanah Pagelen/Bagelen. Di masa Mataram dan Kartasura,
tanah ini masih menjadi wilayah de jure dan menjadi tanah lungguh bagi
pejabat-pejabat kerajaan. Namun demikian, Pagelen/Bagelen kemudian dibagi juga
menjadi milik dua kerajaan saat terjadi Pagiyanti (Perjanjian Giyanti). Menurut
S. Margana, wilayah Siti-Sewu kemudian menjadi milik Kasunanan Surakarta.
Dan tanah Numbak Anyar menjadi milik Kasultanan Ngayogyakarta.
Selanjutnya, mendekati era
Diponegaran (akhir abad 19), wilayah Kedhungkebo/Brengkelan (Purworejo saat ini),
menjadi wilayah Kasunanan Surakarta. Sementara wilayah Semawung (Kutoarjo saat
ini) menjadi wilayah milik Kasultanan Ngayogyakarta. Di sisi barat, wilayah
Panjer menjadi milik Kasunanan Surakarta. Dan wilayah Rema (Jatinegara) menjadi
milik Kasultanan Ngayogyakarta. Di saat pecah Perang Diponegoro, terjadi banyak
perubahan dinamika historis yang menyeret pada timbul-tenggelamnya wilayah-wilayah
di eks-Siti Sewu.
Setelah kekalahan Diponegoro,
pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berusaha merombak total birokrasi saat itu.
Wilayah eks-Siti Sewu yang telah berhasil dianeksasi dari tangan
Kasunanan dan Kasultanan, serta mengganti dinasti penguasa lokal yang berkuasa
atas tanah-tanah di eks-Siti Sewu. Di timur, dinasti Gagak Handaka (Loano)
yang mengerek bendera di belakang Diponegoro, digantikan oleh Resadiwirya (Cakranagara
I), sehingga muncul Purworejo. Di Panjer, Tumenggung Kalapaking IV yang juga
mengerek bendera di belakang Diponegoro harus tumbang, serta digantikan oleh
Tumenggung Arungbinang IV. Secara de facto dan de jure, wilayah eks-Siti
Sewu telah menjadi wewenang pemerintah kolonial Hindia-Belanda.
Dalam upaya menekan sisa-sisa laskar
Diponegoro, maka kemudian dibikin Kabupaten Ambal, pasca 1830, hingga 1870-an. Wilayah
Kabupaten Ambal ini sangat unik, yakni memanjang di sepanjang pesisir dari sisi
selatan Purworejo (disebut Wonoroto), hingga Karangbolong di sisi barat. Termasuk
Bocor juga menjadi wilayah Kabupaten Ambal selama masa itu. Lokasi Bocor yang
terletak di sisi timur Kali Lukulo, secara sosial budaya berbeda dengan wilayah
Kabupaten Ambal di barat Kali Lukulo. Teguh Hindarto, dalam buku Wetan Kali
Kulon Kali, Mengenang Kabupaten Karanganyar Hingga Penggabungan Dengan
Kabupaten Kebumen 1936, mengungkapkan bahwa dikotomi wetan kali-kulon
kali, yang kerap digaungkan masyarakat Kebumen saat ini, sejatinya
merupakan ingatan kolektif terhadap batas wilayah masa lalu daerah-daerah di
Kebumen.
Pasca penghapusan Kabupaten Ambal,
setelah kematian KRAA Purbonegoro (bupati Ambal), wilayah Kabupaten Ambal dibagi
menjadi milik tiga wilayah. Wonoroto dikembalikan kepada Purworejo, Ambal dan
sekitarnya (di sisi timur Lukulo) dikembalikan ke Kebumen, dan
Petanahan-Karangbolong dikembalikan kepada Karanganyar (eks-Rema Jatinegara).
Sehingga secara de jure dan de facto Bocor menjadi wilayah
Kebumen pasca penghapusan Kabupaten Ambal. Regentscap Kebumen dan Karanganyar
berada di bawah Karesidenan Bagelen. Hingga Karesidenan Bagelen dihapuskan pada
1 Agustus 1901, dan dilimpahkan menjadi bagian Karesidenan Kedu.
Di masa Perang Diponegoro,
Ambal-Bocor menjadi pusat pergerakan perang yang sangat mencekam. Dalam tuturan
tradisional, terdapat Gamawijaya yang menjadi pioner perlawanan di daerah
tersebut. Dalam tuturan, Gamawijaya tewas dengan cara dipenggal. Kepalanya kemudian
dipertontonkan ke khalayak. Dengan tewasnya Gamawijaya ini, orang yang berhasil
menumpas kemudian dianugerahi pangkat menjadi bupati Ambal.
Sementara itu menurut sumber
Belanda, dalam buku “De Java Oorlog”, karya P.J.F. Louw dan E.S. de Klerck, tahun
terbit 1894, ditemukan nama Tumenggung Banyakwedi dan Tumenggung Kertabahu yang
sempat memobilisasi pasukannya di Bocor.
Alih
Bahasa:
“Pada
tanggal 25, Buschkens maju ke sisi Bocor di selatan Karanganyar, di mana
Tumengggung Banyakwedi dan Kertabahu telah bersatu. Ekspedisi ini tidak
berhasil seperti sebelumnya, musuh sudah menghilang dan telah pindah ke Desa
Karanganyar. Buschken melanjutkan perjalanan menuju desa itu...” (Louw, P.J.F. & E.S. de Klerck, 1894:
275).
Tentang Gamawijaya yang
disebut-sebut dalam tuturan masyarakat, nampaknya juga merupakan tokoh sejarah
yang nyata. Masih di buku yang sama, kepahlawanan Gamawijaya (di sudut pandang
Bangsa Indonesia), atau pemberontakan Gamawijaya (di sudut pandang Belanda), juga
dicatat secara singkat di buku tersebut.
Dalam pertempuran ini, Letnan
Maxwell melaporkan di sisi pemberontak terdapat 400 orang, termasuk 70 kavaleri
(penunggang kuda), dan pembawa spanduk (panji-panji). Pemberontakan ini dapat
dipadamkan, dan berhasil menangkap salah satu pemimpin perlawanan, yaitu Kamawidjaja,
setelah terjadi perselisihan sengit, yang terus berlanjut bahkan sampai ke
sungai. Tetapi pelokalisasian pertempuran ini tidak berada di Bocor seperti
yang kerap disebut dalam tradisi tutur. Dalam buku yang sama di atas, pertempuran
terjadi di “timur Ambal”. Atas kemenangan Kolonel Colson, kemudian Mayor
Buschkens mempromosikan Colson untuk naik pangkat menjadi mayor.
Di sisi Bocor sendiri, terdapat hal
yang menarik. Pada dekade 80-90-an, daerah Bocor merupakan sentra kerajinan
pandai besi yang besar. Alat-alat pertanian dibuat di bengkel-bengkel sekitaran
Bocor. Serta menjadi alat pertanian yang dikenal memiliki kualitas baik. Namun demikian,
memasuki era industrialisasi alat pertanian, dengan serbuan alat pertanian
hasil industri tempa modern, menjadikan pamor pandai besi di Bocor sangat
memudar.
Tentang pandai besi di Bocor, ini
sangat menarik. Beberapa pandai besi menyatakan bahwa mereka memiliki silsilah berpangkal
dari seorang empu pembuat keris. Bila hal ini dapat diterima, kerajinan pandai
besi di Bocor bisa jadi bermula dari besalen-besalen senjata keris dan tombak
yang berkaitan dengan masa sebelumnya. Namun hal ini harus dibuktikan dengan
penelitian yang lebih komprehensif lagi.
PENUTUP
Pada akhirnya, dinamika sejarah di
Bocor berlangsung dengan sangat lama. Sejak diberitakan dalam naskah-naskah
tradisional, hingga dalam berita-berita Belanda, Bocor senantiasa memiliki kisah
yang menarik. Dinamika sosial budaya yang berlangsung antar zaman menjadikan Bocor
memiliki local history yang patut dijadikan ikon daerah Kabupaten
Kebumen.
Di satu sisi, perlu penelitian lebih
dalam untuk menginterpretasikan sejarah Bocor secara kronologis. Dan peneliti
yang memiliki kompetensi baik, serta obyektif terhadap pelbagai macam sumber
sejarah. Di satu sisi, sejarah Bocor juga bisa menjadi pijakan pemerintah Desa
Bocor dalam menentukan langkah kerja kedepannya. (AP)
***